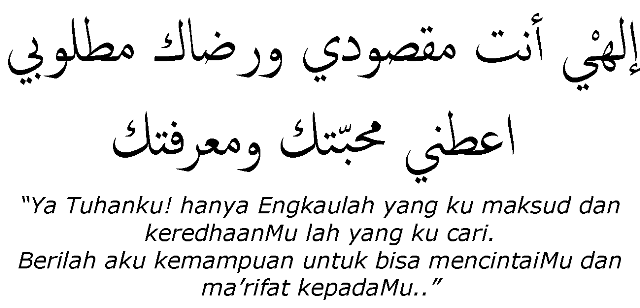HANYA lima kali orang Melayu pergi ke masjid. Saat menikah – itupun ramai yang tak jaga adab -, solat jumaat – itupun masih ada yang mangkir -, solat terawih – itupun awal-awal ramadhan- , pagi lebaran solat eidul fitri dan solat eidul adha.
Ada satu jam lagi solat eidul adha. Rasanya baru kemarin aku melirik ke langit, melihat awan-awan putih berjajaran, pejam celik mata, ‘eidul adha datang lagi, saat aku masih di sini, di bumi orang.
Aku melihat orang-orang memenuhi ruangan solat. Aku memasuki pintu masjid, mengambil tempat di baris hadapan lalu bersolat sunat.
Laungan takbir sahut-sahutan memecah dinihari. Menusuk ke dalam nubari, menyelinap urat darah dan dalam denyut nadiku, dan perasaanku menjadi dua. Sedih dan bangga. Sedih kerna tidak dapat mengucup tangan ibu dan ayah di pagi yang mulia. Namun terselit rasa bangga, kerna pagi ini aku menyambut eidul adha disisi seorang ulamak yang aku cintai dan dicintai ummah. Aku bangga!
Jam sudah menghampiri angka sembilan. Laungan takbir dihentikan menandakan solat bakal bermula. Aku merinding melihat puluhan orang-orang memenuhi ruang masjid. Beberapa orang melangkah masuk dari pintu hadapan berhampiran mimbar masjid dan...ditengah kelibat orang-orang itu aku melihat beliau. Dengan jubah putih dan serban yang ditata rapi, dia melangkah dengan penuh wibawa, mengambil tempat di hadapan. Bilal pun mengisyarat panggilan sembahyang.
“Allahuakbar!” beliau mengimamkan solat.
Semasa membaca ayat-ayat al-Quran, suaranya terdengar serak dan terbata-bata. Seperti hampir hilang ditelan usia. Aku yang menjadi makmum dibelakangnya tersedu sayu. Suara itu terlalu istimewa buatku. Kerna suara itu telah diwakafkan untuk perjuangan Islam, mendedikasikannya dalam wadah Islam, terutama untuk membangun umat yang dahagakan petunjuk Islam. Suara yang diguna ketika melantunkan pesanan di mimbar Jumaat. Suara yang ditiupkan untuk menghidupkan semangat para pendokong perjuangan. Demi Allah! Suara itu menjadi serak dan terbata-bata kerna setiap masa melaungkan semboyang-semboyang jihad. Suara keramat itu akan terus mengalir dalam saluran darahku dan menjadi nadi yang terus berdenyut menghidupkan ruh jihad. Aku jatuh cinta pada suara itu.
Setelah memberi salam beliau naik ke mimbar dan memulakan khutbahnya. Tidak seperti ketika mengimamkan solat, suaranya padu dan penuh semangat di atas mimbar. Dengan suara lantang beliau membawa para hadirin untuk menghayati satu persatu sirah pengorbanan nabi Ibrahim dan sanak keluarganya. Diselangi ayat-ayat al-Quran dan hadis yang diingat dikepala menjadikan pidatonya tajam dan terkesan.
“Marilah kita menyambut hari raya adha, hari raya korban ini, dengan menjadi orang Islam. Menyerah diri kepada Allah. Menerima syariat Allah. Menerima peraturan Allah. Menerima hukum Allah!” tegas beliau penuh semangat. Aku memerhati beliau di atas mimbar dan mendengar setiap butir ucapannya dengan saksama.
“Dan marilah dimusim hari raya haji ini, kita berjanji sebagaimana orang-orang Madinah berjanji untuk berjuang. Menyerahkan diri, harta dan tanah air mereka untuk didirikan kerajaan yang beramal dengan syariat Allah ta’ala. Itulah makna hari raya korban yang perlu difahami oleh kita semua. Marilah kita fahami betul-betul dan laksanakan dengan ikhlas kerana Allah.” Hadirin jadi terpukau dan tersihir dengan kupasan sirah yang diselaraskan dengan realiti perjuangan.
Usai khutbah Eidul Adha, para hadirin berjajaran mengambil kesempatan menyalami beliau. Aku bergerak perlahan di celah puluhan orang-orang, aku ikut berbarisan. Sampai giliranku tiba, aku mencium tangannya dengan takzim. Tidak seperti orang-orang lain. Aku memberanikan mengangkat kepala di hadapannya. Lalu perlahan ku kucup wajahnya yang suci dan bersih itu dengan penuh cinta dan penghormatan sebagai ganti ibu dan ayah. Wajah seorang manusia mulia, wajah yang dicintai penghuni langit dan bumi. Wajah itu sangat istimewa. Wajah itu. Wajah Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang.
Salam Eidul Adha!
Dhiya’
Kuala Terengganu
13 Zulhijjah 1432H